
Ketika Monetisasi dan Narsisme Mengaburkan Kewarasan Publik
Opini, (18/10) - Beberapa waktu terakhir, media sosial ramai memperbincangkan konflik antara Yai Mim dan Sahara di Malang. Awalnya hanya persoalan sosial biasa di lingkungan sekitar, tapi kemudian berubah menjadi tontonan nasional. Potongan-potongan video mereka beredar di mana-mana, disusun sedemikian rupa agar tampak dramatis, penuh emosi, dan memancing komentar. Dalam waktu singkat, ribuan orang ikut bicara, menilai, dan menyimpulkan sesuatu yang belum tentu sesuai kenyataan.
Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa viralitas kini lebih kuat daripada nalar. Begitu sesuatu viral, publik langsung percaya tanpa merasa perlu memeriksa ulang. Yang penting ramai, yang penting menarik. Dan dibalik semua itu, ada motif yang sering tersembunyi, yaitu cuan.
Menariknya, mereka yang ikut menggiring opini bukan orang sembarangan. Banyak dari mereka justru berasal dari kalangan berpendidikan. Paham bagaimana algoritma bekerja, tahu cara membuat narasi menggugah, dan sadar bahwa emosi publik bisa jadi sumber pendapatan. Maka muncullah wajah baru dari demokrasi digital: bukan lagi ruang berbagi gagasan, tapi panggung narsistik yang diatur oleh siapa yang paling banyak ditonton.
Demokrasi yang Intimidatif
Awalnya, media sosial dianggap sebagai wujud kebebasan berbicara. Semua orang punya ruang untuk menyampaikan pendapat. Tapi lama-kelamaan, ruang ini berubah menjadi arena untuk pamer, siapa yang paling vokal, siapa yang paling punya pengaruh, siapa yang paling “tahu segalanya”.
Di titik ini, muncul gejala yang menyerupai Narcissistic Personality Disorder (NPD), kebutuhan berlebihan untuk dikagumi dan dianggap penting. Banyak orang tidak sadar telah terseret ke dalam arus ini. Merasa terlibat karena peduli, padahal yang sebenarnya muncul adalah dorongan untuk tampak benar dan tampak peduli di hadapan publik.
Kasus Yai Mim dan Sahara menjadi contoh nyata. Ribuan komentar bermunculan, seolah-olah semua orang mengenal mereka secara pribadi. Ada yang membela, ada yang mengecam, dan sebagian besar membangun narasi sendiri tanpa data lengkap. Semuanya demi mendapat reaksi, pujian, atau sekadar perhatian.
“Kebenaran Baru” Dalam Dalam Hitungan Detik
Dalam dunia digital, kebenaran sering kali tidak lagi datang dari fakta, melainkan dari seberapa banyak video itu ditonton. Dahlan Iskan menyebutnya sebagai “Kebenaran Baru” kebenaran yang dibangun dari viralitas penggiringan opini.
Potongan video menjadi alat paling ampuh dalam membentuk persepsi. Satu klip bisa menggugah empati, klip lain bisa menimbulkan amarah. Padahal, konteks di baliknya sering hilang. Framing bekerja dengan halus, tidak berbohong, hanya menonjolkan bagian yang menguntungkan.
Begitu video itu menyebar luas, muncul gelombang opini yang sulit dikendalikan. Orang bereaksi spontan tanpa menunggu penjelasan. Yang penting cepat, yang penting ramai. Dalam atmosfer seperti ini, rasionalitas tenggelam di bawah tumpukan komentar.
Narsisme Berbalut Kepedulian
Narsisme di dunia maya tidak selalu tentang pamer wajah atau gaya hidup. Ia bisa muncul dalam bentuk yang lebih lembut, keinginan untuk terlihat lebih bermoral, lebih tahu, atau lebih “berpihak pada kebenaran”. Dalam psikologi disebut sebagai narsisme moral, dorongan untuk menampilkan diri sebagai pembela nilai-nilai luhur, padahal di baliknya ada kebutuhan untuk diakui.
Banyak pengguna media sosial yang mengomentari kasus ini dengan niat baik. Tapi di sisi lain, ada juga yang menikmati sensasi menjadi bagian dari keramaian. Ada rasa puas ketika komentar mereka disukai, atau saat pandangan mereka dianggap paling logis. Di sinilah narsisme digital bekerja, halus, tapi nyata.
Tanpa disadari, empati berubah menjadi tontonan. Penderitaan orang lain dijadikan bahan diskusi, bahkan hiburan. Semua berlomba menunjukkan siapa yang paling “bijak”, padahal tak ada yang benar-benar mencoba memahami persoalan secara utuh.
Cuan Menggeser Nurani
Di balik semua itu, ada mesin besar yang berputar yaitu monetisasi. Setiap klik, setiap komentar, setiap video yang dibagikan bisa menghasilkan uang. Tidak heran jika banyak konten dibuat bukan untuk menyampaikan kebenaran, tapi untuk menarik perhatian sebanyak mungkin.
Konflik menjadi bahan dagangan. Judul-judul sensasional dibuat untuk memancing rasa penasaran: “Yai Mim Menangis di Depan Rumah!”, atau “Sahara Akhirnya Bongkar Rahasia!”. Setiap emosi publik bernilai ekonomi. Semakin besar amarah, semakin besar keuntungan.
Dalam situasi ini, empati kehilangan tempatnya. Yang penting trafik. Yang penting viral. Yang penting menghasilkan.
Nalar yang Lelah
Kalau diperhatikan, netizen kini lebih mudah tersulut emosi daripada berpikir jernih. Media sosial memang dirancang untuk mempercepat reaksi, bukan refleksi. Kita menonton, marah, berkomentar, lalu scroll ke video berikutnya. Tak sempat berpikir panjang.
Padahal, di balik semua kehebohan itu, ada manusia yang sungguh-sungguh terluka. Ada kehidupan nyata yang tidak bisa diselesaikan dengan like atau komentar. Tapi semua itu sering tenggelam dalam hiruk pikuk algoritma yang haus interaksi.
Ketika nalar publik lelah, yang tersisa adalah kebisingan. Kita marah, lalu lupa. Kita simpati, lalu berpaling. Semua berlangsung cepat, dangkal, dan sementara.
Saatnya Menyepi dari Riuh
Barangkali kita tak bisa sepenuhnya lepas dari arus viralitas. Tapi kita bisa mulai menyepi sejenak dari riuh, menonton dengan jarak, dan bertanya: “Apakah ini benar? Atau hanya rekayasa emosi?”
Kita bisa memilih untuk tidak langsung bereaksi, tidak ikut menilai sebelum paham konteks. Tidak harus membela atau menyerang. Kadang, cukup diam dan belajar dari peristiwa yang terjadi.
Viralitas tidak akan berhenti. Tapi setidaknya, kita bisa memilih untuk tidak ikut menambah kabut. Karena pada akhirnya, dunia digital hanya sekuat nalar orang-orang yang menggunakannya. Dan jika kita bisa menahan diri dari keinginan untuk tampil, dari godaan cuan, dari dorongan ingin selalu benar mungkin disitulah kewarasan publik bisa mulai tumbuh kembali.[*]
 SMA NEGERI 1 MONTONG
SMA NEGERI 1 MONTONG




_11zon_11zon-100x100.jpeg)









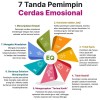
-100x100.jpeg)
