
Ancaman Kekuatan Narasi di Media Sosial: Kebenaran Baru dalam Konflik Sosial Kehidupan Nyata
Opini, (12/10) - Media sosial saat ini bukan sekadar tempat berbagi informasi, tetapi menjadi ruang produksi makna dan opini publik yang begitu cepat berubah. Di dalamnya, narasi bukan hanya menyampaikan realitas, melainkan menciptakan realitas. Inilah yang oleh Dahlan Iskan disebut sebagai “Kebenaran Baru” — sebuah fenomena ketika persepsi publik yang terbentuk dari narasi viral di media sosial dianggap lebih benar dibanding fakta yang sebenarnya. Fenomena ini nyata dalam banyak kasus sosial, termasuk yang terbaru: konflik antara Yai Mim dan Sahara di Malang.
Kasus yang semula hanya persoalan sosial bertetangga menjelma menjadi isu nasional. Semuanya bermula dari unggahan video di media sosial yang menampilkan potongan interaksi antara dua pihak, tanpa konteks utuh. Dalam hitungan jam, jutaan mata menonton, ribuan komentar muncul, dan masyarakat membentuk opini sendiri. Narasi terbentuk—bukan berdasarkan bukti hukum, melainkan dari potongan cerita yang paling dulu viral. Dari sinilah ancaman kekuatan narasi di media sosial menjadi nyata.
Kebenaran yang Diciptakan: Dari Fakta ke Persepsi
Dalam teori komunikasi, narasi memiliki daya membentuk realitas karena manusia lebih mudah mempercayai cerita daripada data. Ketika seseorang melihat video dengan emosi kuat—kemarahan, tangisan, atau tuduhan—maka ia cenderung mempercayainya tanpa menyelidiki lebih dalam. Dahlan Iskan menyebut kondisi ini sebagai munculnya “kebenaran baru”: kebenaran yang lahir dari persepsi kolektif masyarakat digital, bukan dari proses klarifikasi dan pembuktian.
Kebenaran baru ini sangat berbahaya karena tidak lagi membutuhkan verifikasi. Begitu narasi tersebar luas, ia menjadi “fakta sosial” yang mempengaruhi pandangan publik. Dalam kasus Yai Mim dan Sahara, publik lebih dulu percaya pada narasi yang beredar di TikTok, yang menggambarkan Yai Mim sebagai pelaku intimidasi dan perilaku tak pantas terhadap tetangganya. Video tersebut menimbulkan empati kepada Sahara, yang dianggap korban. Namun, ketika fakta baru dan klarifikasi muncul belakangan, publik sudah terlanjur menghakimi.
Fenomena ini membuktikan bahwa di dunia digital, yang pertama muncul sering kali dianggap paling benar. Padahal, dalam etika komunikasi dan hukum, kebenaran seharusnya lahir dari keseimbangan dua sisi, bukan dari kecepatan unggah konten.
Ketika Narasi Menjadi Senjata Sosial
Narasi di media sosial bersifat demokratis: siapa pun bisa membuat, menyebarkan, dan memperkuatnya. Namun, justru di sinilah letak ancamannya. Dalam konflik sosial seperti Yai Mim vs Sahara, media sosial memperluas ruang konflik, dari halaman rumah menjadi ruang nasional.
Video yang viral tidak hanya membentuk opini publik, tetapi juga menekan psikologis, sosial, dan hukum pihak yang diberitakan. Yai Mim, yang sebelumnya dikenal sebagai dosen dan tokoh agama, tiba-tiba kehilangan reputasi, bahkan diusir dari lingkungannya. Ia bukan hanya berhadapan dengan tetangga, tetapi dengan jutaan netizen yang menilai tanpa mengenalnya.
Narasi negatif di media sosial bekerja seperti arus deras: cepat, emosional, dan sulit dikendalikan. Sekali seseorang menjadi target, hampir mustahil untuk memperbaiki citra diri di hadapan publik yang sudah memiliki “kebenaran” versi mereka sendiri. Dalam konteks ini, media sosial tidak lagi menjadi ruang kebebasan berekspresi, melainkan medan trial by public opinion atau pengadilan opini publik yang keputusannya lebih kejam dari hukum formal.
Viralitas yang Menelan Nalar
Kasus Yai Mim dan Sahara menunjukkan bagaimana persoalan pribadi bisa meledak menjadi perdebatan nasional. Isu sederhana, tanah parkir, akses jalan, dan ucapan antar tetangga menjadi bahan pemberitaan berhari-hari. Setiap potongan video dijadikan bukti moral, setiap komentar dijadikan penghakiman.
Narasi viral bukan lagi sekadar berita, tetapi drama sosial yang disaksikan oleh seluruh negeri. Penonton bukan sekadar mengamati, tetapi ikut menentukan siapa yang “benar” dan siapa yang “salah.” Dalam logika media sosial, kebenaran bukan lagi hasil proses rasional, tetapi hasil konsensus emosional: siapa yang lebih menyentuh perasaan publik, dialah yang menang.
Dahlan Iskan, dalam salah satu tulisannya, menyebut fenomena ini sebagai “pergeseran pusat kebenaran.” Dulu, kebenaran dicari di ruang sidang dan ruang redaksi; kini, ia diputuskan di kolom komentar dan algoritma. Masyarakat tidak lagi menunggu bukti, tetapi menunggu siapa yang unggah duluan. Inilah bentuk baru kekuasaan: kekuasaan narasi.
Hilangnya Nalar Kolektif dan Keadilan Digital
Ketika narasi menjadi penguasa, kebenaran objektif perlahan memudar. Bahayanya, masyarakat bisa kehilangan kemampuan berpikir kritis. Publik yang terbiasa menelan narasi viral tanpa refleksi akan mudah digiring ke arah tertentu—baik oleh emosi, kepentingan politik, maupun algoritma media sosial.
Fenomena ini menimbulkan efek domino, reputasi seseorang bisa hancur dalam satu malam, hubungan sosial bisa retak karena komentar warganet, bahkan lembaga hukum pun tertekan oleh opini publik. Kasus Yai Mim adalah cerminan bahwa kecepatan narasi bisa mengalahkan keadilan.
Lebih jauh lagi, “kebenaran baru” yang diciptakan media sosial tidak selalu bisa dikoreksi. Begitu narasi negatif melekat, ia hidup selamanya di jejak digital. Meskipun klarifikasi, mediasi, atau permintaan maaf telah dilakukan, masyarakat cenderung mengingat versi pertama yang viral. Dalam dunia digital, memaafkan itu lambat, melupakan itu mustahil.
Kritisisme Digital: Menyelamatkan Kebenaran dari Narasi
Untuk menghadapi ancaman kekuatan narasi ini, masyarakat perlu memiliki kritisisme digital yaitu kemampuan untuk berpikir sebelum bereaksi, menimbang sebelum menyebarkan. Literasi media harus mengajarkan publik untuk tidak mudah percaya pada potongan cerita, karena kebenaran sejati tidak pernah hadir dalam 30 detik video.
Platform media sosial juga harus bertanggung jawab. Algoritma yang hanya mengedepankan sensasi harus mulai memberi ruang bagi konteks dan klarifikasi. Jurnalisme digital harus mengembalikan peran verifikasi dan keseimbangan, bukan sekadar mengejar klik dan viralitas.
Sebagai pengguna, kita pun harus belajar menahan diri. Tidak terburu-buru menjadi hakim dalam drama sosial orang lain. Setiap unggahan punya konsekuensi, setiap komentar bisa menyakiti. Ketika narasi menjadi alat yang destruktif, maka kita semua turut bersalah jika diam saja.
Kebenaran sejati tidak seharusnya digantikan oleh “kebenaran baru” yang lahir dari algoritma dan emosi kolektif. Dalam kasus Yai Mim dan Sahara, kita belajar bahwa media sosial bisa menjadi pisau bermata dua, bisa membuka ruang transparansi, tapi juga menelanjangi kemanusiaan.
Di tengah derasnya arus narasi digital, tugas kita bukan sekadar menjadi konsumen cerita, tetapi penjaga nalar. Sebab jika masyarakat terus membiarkan narasi menggantikan fakta, maka yang kita hadapi bukan lagi dunia informasi, melainkan dunia ilusi. Dan ketika kebenaran bergantung pada siapa yang paling viral, maka keadilan akan selalu datang terlambat.[*]
 SMA NEGERI 1 MONTONG
SMA NEGERI 1 MONTONG



_11zon_11zon-100x100.jpeg)










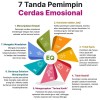
-100x100.jpeg)
